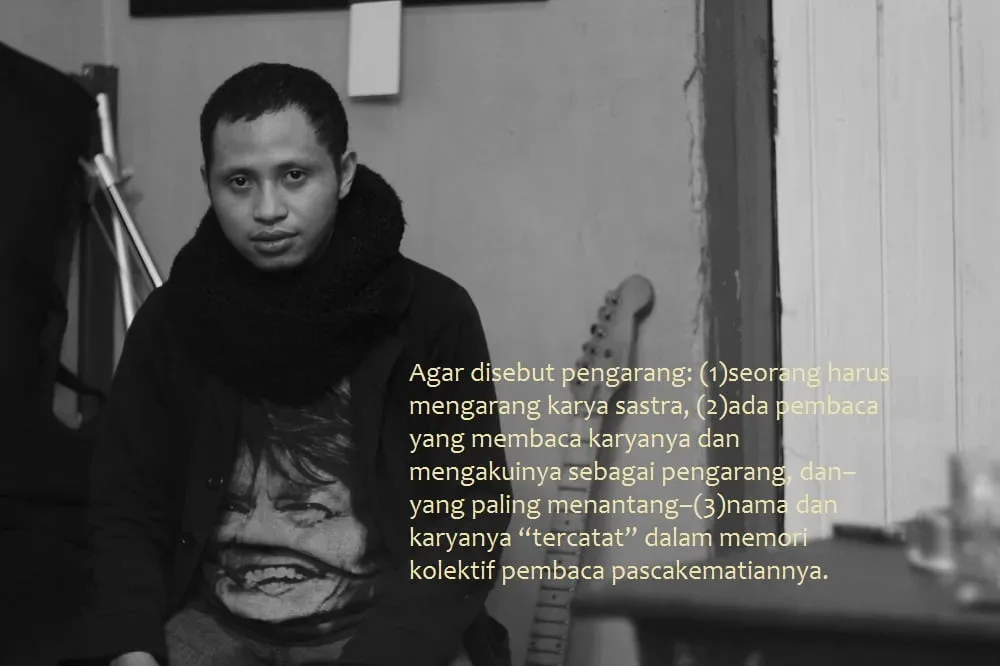Tentang sastra dan sastrawan NTT cukup ramai dibicarakan akhir-akhir ini. Ada banyak pertanyaan, seperti: siapakah pengarang NTT, sudah tepatkah beberapa nama disebut sebagai sastrawan?
Dalam usaha mencari cara membaca yang lain tentang pengarang NTT, Blog Ranalino.co menampilkan tulisan menarik yang dibuat oleh Marcelus Ungkang, dosen sastra di STKIP St. Paulus Ruteng. Tulisan ini sebelumnya pernah disiarkan di blog pribadi. Atas izin penulis di-repost di laman ini. Selamat menyimak!
Soal Pengarang NTT
Oleh: Marcelus Ungkang
Jika saya membuat karya sastra, apakah saya sudah dapat disebut pengarang? Pertanyaan klasik tersebut layak dipikirkan kembali dalam konteks sastra di NTT karena dua alasan. Pertama, pada era digital kepengarangan bukan lagi dunia yang ekslusif dan mahal secara produksi seperti di era cetak. Setiap orang, yang memiliki akses pada teknologi informasi, relatif mudah dapat menerbitkan dan menyebarkan karyanya secara luas.
Problemnya, fenomena tersebut diikuti dengan penyempitan diskursus kepengarangan pada dimensi produksi semata. Kedua, makin banyaknya karya sastra dan kegiatan sastra di NTT perlu didukung dengan menciptakan lingkungan kritik yang sehat.
Tiga Cara Mendefinisikan Pengarang
Ada tiga perspektif yang bisa digunakan untuk menjelaskan siapa pengarang: sejarah sastra, sosiologi sastra, dan pascastrukturalisme (Derrida, Foucault, dan Barthez). Tulisan ini dibatasi pada perspektif sejarah sastra dan sosiologi sastra.
Dengan menyalingtunjangkan sejarah sastra dan sosiologi sastra, ada tiga cara untuk mendefinisikan siapa pengarang NTT itu. Cara pertama adalah melalui jalur genesis: pengarang adalah orang yang menciptakan karya sastra. Jika seseorang ingin disebut pengarang, ia harus menciptakan karya sastra. Atas dasar itu pula salah satu kerja sosiologi sastra mendefinisikan pengarang adalah pendataan karya-karya sastra yang terbit.
Definisi di atas banyak dikritik karena mereduksi soal kepengarangan pada dimensi subjektif semata. Pasalnya, dengan definisi itu, siapa saja, sepanjang bisa menghasilkan karya sastra, bisa menyebut dirinya sendiri sebagai pengarang. Hal yang diabaikan dari definisi ini adalah dimensi intersubjektif dari dunia kepengarangan.
Seseorang disebut sebagai pengarang bukan karena semata dirinya menciptakan karya, melainkan karena ada subjek lain yang juga menyebutnya sebagai pengarang. Lalu siapakah subjek lain yang dimaksud itu? Pertanyaan tersebut berkaitan dengan cara kedua dalam mendefinisikan pengarang, yaitu resepsi pembaca. Melalui jalur ini definisi siapakah pengarang dihadapkan pada peran pembaca dalam dalam pendefinisian pengarang. Seseorang disebut sebagai pengarang karena ada pembaca atau komunitas pembaca yang “mengakui” bahwa seseorang adalah pengarang.
Baca juga: Orang-Orang Muda Hebat di Kupang
Jika menggunakan logika oposisi, arti kepengarangan itu didapatkan dari relasi perbedaannya dengan pembaca: tidak ada pengarang tanpa pembaca, dan sebaliknya. Pembaca itu sendiri perkara yang kompleks jika didekati dengan resepsi sastra model penampang sinkronik Jauss.
Untuk mendapatkan visualisasi penampang sinkronis ini, mari bayangkan kembali ilustrasi sebuah batang pohon yang telah ditebang yang dikemukakan Saussure hampir seabad silam. Pada batang pohon yang telah ditebang itu terdapat garis-garis melingkar yang menandakan usia dari pohon itu. Masing-masing lingkaran itu dapat kita katakan sebagai sebuah periode dalam sejarah sastra.
Hal yang perlu dicatat: sejarah sastra tidak selalu pararel dengan sejarah umum (Teeuw, 1984). Jika seorang peneliti meneliti perkembangan sastra dari suatu lingkaran awal yang ditentukan sampai ke lingkaran masa peneliti itu hidup (baca: dari masa ke masa), itulah yang disebut pendekatan diakronik. Namun, jika peneliti hanya meneliti pada suatu lingkaran tertentu (baca: kurun waktu tertentu), itulah pendekatan sinkronik.
Model penampang sinkronik Jauss, meski pada zamannya dipuji (1970-an), juga tidak luput dari kritik. Ada dua pokok kritik terhadap Jauss.
Pertama, pembaca seperti apa yang dimaksud oleh Jauss kurang jelas. Persis pada hal tersebut juga menjadi pertanyaan besar di NTT: siapakah dan seperti apakah pembaca sastra di NTT?
Kedua, keterbatasan pendekatan sinkronik adalah karena ada karya sastra yang kurang disorot pada suatu masa, tetapi baru dikenal atau dibicarakan pembaca pada masa-masa berikutnya. Sebagai contoh, karya-karya lama Pramoedya, karena larangan rezim Orde Baru, justru baru booming di Indonesia pada era reformasi. Karena itu, perspektif ketiga yang sifatnya diakronis menjadi relevan.
Dalam perspektif diakronik definisi pengarang dilihat sejak karya-karyanya muncul sampai pada puncaknya, dalam analisis statistik Lehman (Escarpit, 2008:,40), yaitu 35 sampai 40 tahun pascakematian pengarang. Pokok pertanyaannya, apakah 35 sampai 40 tahun setelah pengarang itu meninggal sosok atau karyanya masih dibaca atau dibicarakan.
Baca juga: Apa itu Berita?
Pada perspektif itu, ketercatatan kepengarangan sastrawan bukan pada katalog semata, melainkan pada memori kolektif pembaca (bdk. Escarpit, 2008:34). Kita bisa bertanya kepada pembaca, misalnya, apakah mereka membaca karya dari Gerson Poyk, John Dami Mukese, Maria Mathildis Banda, atau Mario F. Lawi.
Siapakah Pengarang NTT; Jalan Moderat
Dalam cara yang lebih moderat lebih baik jika tiga cara itu dilihat sebagai lapis filter dalam pendefinisian pengarang, alih-alih jalur yang berbeda. Agar disebut pengarang: (1)seorang harus mengarang karya sastra, (2)ada pembaca yang membaca karyanya dan mengakuinya sebagai pengarang, dan–yang paling menantang–(3)nama dan karyanya “tercatat” dalam memori kolektif pembaca pascakematiannya.
Melalui cara pandang lapis filter tersebut juga bisa terlihat bidang penelitian yang perlu dikerjakan oleh para peneliti sastra di NTT, yaitu resepsi pembaca dan kajian diakronis. Perlu ada penelitian sejauh mana pembaca meresepsi karya pengarang NTT dari waktu ke waktu. Siapa sajakah yang tercatat dalam memori kolektif pembaca sastra di NTT?
Ikhwal resepsi pembaca, secara politis bisa dilihat sebagai advokasi peran pembaca dalam sistem sastra di NTT. Tanpa pembaca, wacana kepengarangan ibarat masturbasi: ditulis sendiri, dibaca sendiri, dan (sering) dipuji sendiri. Sayangnya, toh itu juga ilusi karena setiap masturbasi selalu mengandaikan adanya “yang lain”. Anda tidak bisa bercinta dengan diri sendiri, bukan? (*)
–
4 Februari 2017
Marcelus Ungkang adalah pendiri Teater Saja, sebuah komunitas teater di Ruteng.